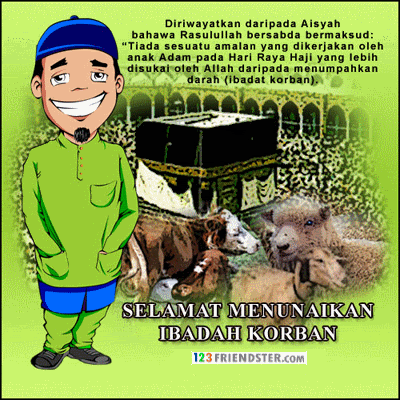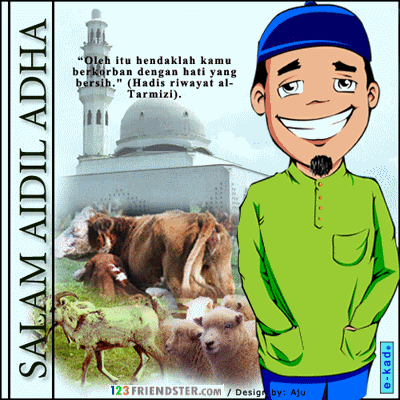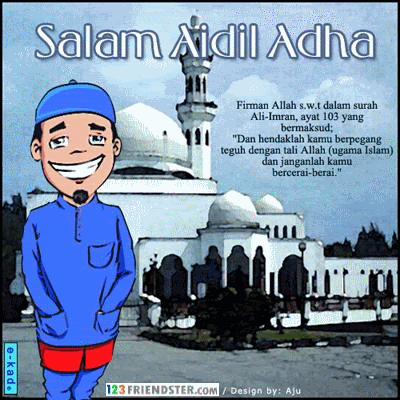عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا
Dari Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabada: ”Apabila telah masuk sepuluh (hari pertama bulan Dzulhijjah), salah seorang di antara kalian ingin berqurban, maka janganlah sedikit pun ia menyentuh (memotong) rambut (bulu)nya dan mengupas kulitnya.”
Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad-nya no. 25269, Al-Imam Muslim no. 1977, Al-Imam An-Nasa`i, 7 hal. 212, Al-Imam Abu Dawud 3/2793, Al-Imam At-Tirmidzi 3/1523, Al-Imam Ibnu Majah 2/3149, Al-Imam Ad-Darimi no. 1866. (CD Program, Syarh An-Nawawi cet. Darul Hadits)
Jalur Periwayatan Hadits
Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan Sa’id bin Musayyib dari Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha. Dalam riwayat hadits ini terdapat seorang rawi yang diperselisihkan penyebutan namanya, yaitu ‘Umar bin Muslim Al-Junda’i. Ada yang menyebutnya ‘Umar bin Muslim dan ada pula yang menyebutnya ‘Amr bin Muslim.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu menerangkan, riwayat ‘Umar bin Muslim dari Sa’id bin Musayyab, pada nama عمر kebanyakan riwayat menyebutnya dengan mendhammah ‘ain (عُمر) ‘Umar, kecuali riwayat dari jalan Hasan bin ‘Ali Al-Hulwani, menyebutkan dengan memfathah ‘ain (عَمرو) ‘Amr. Dan ulama menyatakan bahwa keduanya ada penukilannya. (lihat Syarh Al-Imam An-Nawawi, 7/155)
Sebaliknya, Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu menyatakan, telah terjadi perselisihan dalam penyebutan ‘Amr bin Muslim. Sebagian menyatakan ‘Umar dan kebanyakan menyatakan ‘Amr. Beliau sendiri menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa dia adalah ‘Amr bin Muslim bin Ukaimah Al-Laitsi Al-Junda’i. (lihat ‘Aunul Ma’bud, 5/224, cet. Darul Hadits)
Al-Hafizh Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullahu mengatakan: “Telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan manusia terhadap hadits ini, baik dari sisi riwayat maupun dirayah (kandungan maknanya). Sebagian berkata: Tidak benar kalau hadits ini kedudukannya marfu’ (sampai kepada nabi), yang benar ialah mauquf (hanya sampai kepada shahabat).
Ad-Daruquthni rahimahullahu berkata dalam kitab Al-‘Ilal: Telah meriwayatkan secara mauquf Abdullah bin ‘Amir Al-Aslami, Yahya Al-Qathan, Abu Dhamrah, semuanya dari Abdurrahman bin Humaid, dari Sa’id. ‘Uqail meriwayatkan secara mauquf sebagai ucapan Sa’id. Yazid bin Abdillah dari Sa’id dari Ummu Salamah, sebagai ucapan Ummu Salamah. Demikian pula Ibnu Abi Dzi`b meriwayatkan dari jalan Al-Harts bin Abdurrahman, dari Abu Salamah, dari Ummu Salamah, sebagai ucapannya. Abdurrahman bin Harmalah, Qatadah, Shalih bin Hassan, semuanya meriwayatkan dari Sa’id, sebagai ucapannya. Riwayat yang kuat dari Al-Imam Malik, menyatakan mauquf. Dan Al-Imam Ad-Daruquthni berkata: “Yang benar menurut saya adalah pendapat yang menyatakan mauquf.”
Pendapat kedua menyatakan yang benar adalah marfu’. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Al-Imam Muslim ibn Hajjaj rahimahullahu, seperti yang beliau sebutkan dalam kitab Shahih-nya. Demikian pula Abu ‘Isa At-Tirmidzi rahimahullahu berkata: “Hadits ini hasan shahih.” Ibnu Hibban rahimahullahu juga meriwayatkan dalam Shahih-nya.
Abu Bakr Al-Baihaqi rahimahullahu berkata: “Hadits ini telah tetap/kuat sebagai hadits yang marfu’ ditinjau dari beberapa sisi. Di antaranya: Tidak mungkin orang yang seperti mereka (para ulama yang menshahihkan) salah. Al-Imam Muslim rahimahullahu telah menyebutkan dalam kitabnya. Selain mereka juga masih ada yang menshahihkannya. Telah meriwayatkan secara marfu’ Sufyan bin Uyainah dari Abdurahman bin Humaid dari Sa’id dari Ummu Salamah dari Nabi, dan Syu’bah dari Malik dari ‘Amr bin Muslim dari Sa’id dari Ummu Salamah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan tidaklah kedudukan Sufyan dan Syu’bah di bawah mereka yang meriwayatkan secara mauquf. Tidaklah lafadz/ucapan hadits seperti ini merupakan ucapan dari para shahabat, bahkan terhitung sebagai bagian dari sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti sabda beliau (لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dan yang semisalnya.” (lihat ‘Aunul Ma’bud, 5/225 cet. Darul Hadits, Mesir)
Penjelasan Hadits
(إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ) artinya, apabila telah masuk sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.
Makna ini dipahami dari riwayat lain yang menyebutkan:
إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ
”Apabila kalian telah melihat hilal di bulan Dzulhijah.”
atau:
فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ
”Apabila telah terlihat hilal bulan Dzulhijjah.”
(وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) artinya, salah seorang di antara kalian ingin berqurban.
Pada sebagian riwayat terdapat tambahan lafadz (وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ), di sisinya (punya) hewan sembelihan. Pada lafadz yang lain (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ), barangsiapa punya hewan sembelihan yang akan dia sembelih.
(فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) artinya, janganlah sedikitpun ia menyentuh (memotong) rambut (bulu) nya dan mengupas kulitnya.
Pada riwayat yang lain terdapat lafadz (فَلاَ يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلاَ يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا), Janganlah sekali-kali ia mengambil rambut dan memotong kuku.
Pada lafadz yang lain:
(فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) Hendaknya ia menahan dari memotong rambut dan kukunya.
Dalam lafadz yang lain:
فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ
Janganlah sekali-kali ia mengambil rambut dan memotong kukunya sedikitpun, hingga ia menyembelih.
Sunnah yang Terabaikan
Termasuk sunnah yang terabaikan bagi seorang yang telah memiliki hewan qurban yang akan ia sembelih adalah tidak ada pengetahuan tentang apa yang harus ia perbuat apabila telah masuk tanggal 1 hingga 10 Dzulhijjah (hari raya qurban tiba)! Tidak/belum sampainya suatu ilmu seringkali menjadi penyebab terabaikannya sekian banyak sunnah (kebaikan) baik berupa perintah atau larangan. Oleh sebab itu, sepantasnya bahkan wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun wanita untuk membekali kehidupan ini dengan ilmu agama yang benar, hingga tidak berujung penyesalan hidup di kemudian hari.
Hadits yang tersebut di atas membimbing kita, terutama bagi seorang muslim yang telah mempersiapkan hewan qurban untuk disembelih pada hari raya qurban atau setelahnya pada hari-hari Tasyriq (tanggal 11,12,13 Dzulhijjah). Apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, hendaknya ia menahan diri untuk tidak mencukur atau mencabut rambut/bulu apapun yang ada pada dirinya (baik rambut kepala, ketiak, tangan, kaki, dan yang lainnya). Demikian pula tidak boleh memotong kuku (tangan maupun kaki) serta tidak boleh mengupas kulit badannya (baik pada telapak tangan maupun kaki, ujung jari, tumit, atau yang lainnya). Larangan ini berlaku bagi yang memiliki hewan qurban dan akan berqurban, bukan bagi seluruh anggota keluarga seseorang yang akan berqurban. Larangan ini berakhir hingga seseorang telah menyembelih hewan qurbannya. Jika ia menyembelih pada hari yang kesepuluh Dzulhijjah (hari raya qurban), di hari itu boleh baginya mencukur rambut/memotong kuku. Jika ia menyembelih pada hari yang kesebelas, keduabelas, atau yang ketigabelas, maka di hari yang ia telah menyembelih hewan qurban itulah diperbolehkan baginya untuk mencukur rambut atau memotong kuku.
Dalam sebuah riwayat yang terdapat dalam Shahih Muslim, ‘Amr bin Muslim pernah mendapati seseorang di kamar mandi sedang mencabuti bulu ketiaknya menggunakan kapur sebelum hari raya qurban. Sebagian mereka ada yang berkata: “Sesungguhnya Sa’id bin Musayyib tidak menyukai perkara ini.”
Ketika ‘Amr bin Muslim bertemu dengan Sa’id bin Musayyib, ia pun menceritakannya. Sa’id pun berkata: “Wahai anak saudaraku, hadits ini telah dilupakan dan ditinggalkan. Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyampaikan kepadaku, ia berkata: Nabi telah bersabda, seperti hadits di atas.”
Kalau manusia di zaman beliau demikian keadaannya, bagaimana dengan di zaman kita sekarang?!
Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang menghidupkan Sunnah Nabi-Nya dan bukan menjadikan sebagai orang yang memadamkan/mematikannya.
Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi larangan dalam perkara ini. Ada yang memahami sesuai dengan apa yang nampak dari lafadz hadits tersebut, sehingga mereka berpendapat haram bagi seseorang untuk melakukannya (wajib untuk meninggalkannya). Di antara mereka adalah Sa’id bin Musayyib, Rabi’ah bin Abi Abdirrahman, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan sebagian dari pengikut Al-Imam Asy-Syafi’i. Adapun Al-Imam Asy-Syafi’i dan pengikutnya berpendapat makruh (tidak dikerjakan lebih utama), bukan diharamkam. Dan yang berpendapat semisal ini adalah Al-Imam Malik dan sebagian pengikut Al-Imam Ahmad seperti Abu Ya’la dan yang lainnya.
Pendapat lain dalam hal ini adalah mubah (tidak mengapa melakukannya). Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah dan pengikutnya.
Peringatan
Sebagian orang ada yang memahami bahwa larangan mencukur rambut/bulu, memotong kuku, dan mengupas/mengambil kulit, kata ganti dalam hadits di atas (-nya - bulunya, kukunya, kulitnya) kembali kepada hewan yang akan disembelih.
Jika demikian, hadits di atas akan bermakna: “Apabila telah masuk 10 hari awal Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian akan berqurban, maka janganlah ia mencukur bulu (hewan yang akan dia sembelih), memotong kuku (hewan qurban), dan jangan mengupas kulit (hewan qurban).”
Tentunya bukanlah demikian maknanya. Makna ini juga tidak selaras dengan hikmah yang terkandung di dalam hadits itu sendiri.
Hikmah yang Terkandung
Di samping sebagai salah satu bentuk ketaatan dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, hikmah dari larangan tersebut adalah agar seseorang tetap utuh anggota badannya kala ia akan dibebaskan dari panasnya api neraka.
Sebagian ada yang berpendapat, hikmahnya adalah agar seorang merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji atau diserupakan dengan seorang yang telah berihram, sehingga mereka juga dilarang dari mencukur rambut, memotong kuku, mengupas kulit, dan sebagainya.
Namun pendapat terakhir ini ada yang tidak menyetujuinya, dengan alasan, bagaimana diserupakan dengan seorang yang menunaikan haji, sementara ia (orang yang akan berqurban) tidak dilarang dari menggauli istrinya, memakai wewangian, mengenakan pakaian dan yang lainnya. (lihat ‘Aunul Ma’bud 5/224-226, cet. Darul Hadits, Syarh An-Nawawi 7/152-155, cet. Darul Hadits)
Hadits-hadits Lemah dalam Berqurban
1. Kesempurnaan sembelihan
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ بِيَوْمِ اْلأَضْحَى عِيْدًا جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ اْلأُمَّةِ. قَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أُضْحِيَّةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
Dari Abdullah bin ‘Amr bin Al-’Ash radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Aku diperintahkan pada hari Adha sebagai hari raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkannya untuk umat ini.” Seorang sahabat bertanya: “Bagaimana pendapatmu (kabarkan kepada saya) jika aku tidak mendapatkan kecuali sembelihan hewan betina, apakah aku menyembelihnya?” Beliau menjawab: “Jangan. Akan tetapi ambillah dari rambut dan kukumu, cukur kumis serta bulu kemaluanmu. Itu semua sebagai kesempurnaan sembelihanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. Abu Dawud no. 2786)
Al-Mundziri rahimahullahu menjelaskan: “Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Sanad hadits ini lemah di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama ‘Isa bin Hilal Ash-Shadafi. Tidak ada yang menguatkan kecuali Ibnu Hibban.”
Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu mendhaifkannya dalam Dha’if Abi Dawud. (lihat ‘Aunul Ma’bud 5/222)
2. Sembelihan dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal
عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ
Dari Hanasy ia berkata: “Aku melihat ‘Ali bin Abi Thalib sedang menyembelih dua ekor domba. Kemudian aku bertanya: ‘Apa ini?’ Ali pun menjawab: ‘Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mewasiatkan kepadaku agar aku menyembelih hewan qurban untuknya, dan akupun menyembelihkan untuknya.” (HR. Abu Dawud no. 2786, At-Tirmidzi no. 1495)
Sanad hadits ini lemah, terdapat di dalamnya seorang rawi yang bernama Abul Hasna`, yang dia tidak dikenal. (lihat ‘Aunul Ma’bud 5/222)
3. Pahala bagi orang yang berqurban
فِي اْلأُضْحِيَّةِ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Pada setiap hewan qurban, terdapat kebaikan di setiap rambut bagi pemiliknya.” (HR. At-Tirmidzi. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu berkata: “Hadits ini maudhu’ (palsu).”)
4. Hewan qurban adalah tunggangan di atas shirath
اسْتَفْرِهُوْا ضَحَايَاكُمْ، فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلىَ الصِّرَاطِ
“Perbaguslah hewan qurban kalian, karena dia adalah tunggangan kalian di atas shirath.”
Hadits ini lemah sekali (dha’if jiddan). Dalam sanadnya ada Yahya bin Ubaidullah bin Abdullah bin Mauhab Al-Madani, dia bukanlah rawi yang tsiqah, bahkan matrukul hadits (haditsnya ditinggalkan oleh para ulama). Juga ayahnya, Ubaidullah bin Abdullah, adalah seorang yang majhul. Lihat Adh-Dha’ifah karya Al-Albani rahimahullahu (2/14, no. hadits 527, dan 3/114, no. hadits 1255), Dha’iful Jami’ (no. 824). (Ahkamul Udh-hiyyah hal. 60 dan 62, karya Abu Sa’id Bal’id bin Ahmad)
عَظِّمُوا ضَحَايَاكُمْ فِإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ
“Gemukkanlah hewan qurban kalian, karena dia adalah tunggangan kalian di atas shirath.”
Hadits dengan lafadz ini tidak ada asalnya. Ibnu Shalah rahimahullahu berkata: “Hadits ini tidak dikenal, tidak pula tsabit (benar datang dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam).” (Ahkamul Udh-hiyyah hal. 64, karya Abu Sa’id Bal’id bin Ahmad)
5. Darah sembelihan jatuh di tempat penyimpanan Allah Subhanahu wa Ta'ala
أَيُّهَا النَّاسُ، ضَحُّوْا وَاحْتَسِبُوْا بِدِمَائِهَا، فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي اْلأَرْضِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
“Wahai sekalian manusia, berqurbanlah dan harapkanlah pahala dari darahnya. Karena meskipun darahnya jatuh ke bumi namun sesungguhnya dia jatuh ke tempat penyimpanan Allah Subhanahu wa Ta'ala.” (HR. Ath-Thabarani dalam Al-Mu’jamul Ausath)
Hadits ini maudhu’ (palsu). Dalam sanadnya ada ‘Amr bin Al-Hushain Al-’Uqaili, dia matrukul hadits, sebagaimana dinyatakan Al-Haitsami rahimahullahu. Lihat Adh-Dha’ifah karya Al-Albani rahimahullahu (2/16, no. hadits 530). (Ahkamul Udh-hiyyah hal. 62, karya Abu Sa’id Bal’id bin Ahmad)
Wallahu ta’ala a’lam.